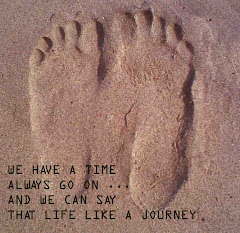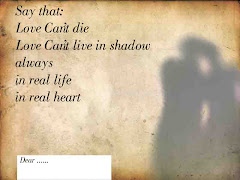ABSTRAKSI
Pemberdayaan masyarakat Indonesia yang mengacu kepada civil society merupakan sebuah gerakan yang saat ini menjadi salah satu wacana dalam pembangunan bangsa menuju peradaban rakyat. Di sini bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa dan budaya merupakan satu tantangan tersendiri dalam pemberdayaan civil society. Namun hal itu bukanlah satu tantangan berarti ketika ada kesatuan persepsi yang terangkum dalam satu pandangan sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut yang melatar belakangi penulisan ini. Pembahasan ini bertujuan untuk melengkapi strategi pemberdayaan civil society yang sudah diaplikasikan dan memberikan satu dasar pemberdayaan yang lebih kultural sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di era perkembangan global dewasa ini.
Tendensi konseptual perihal konsep civil society dan etnisitas ini, dijelaskan oleh beberapa ahli dari luar dan kaum intelektual Indonesia yang memiliki perhatian pada masalah pemberdayaan civil society. Bagian ini menjabarkan terminologi civil society. Dijelaskan juga kharakteristik, esensi, dan tantangan-tantangan dalam pemberdayaan civil society itu sendiri. Dalam kerangka pembahasan konsep, wacana etnisitas jabarkan sebagai sebuah konsep yang lebih mengacu pada teori Webber. Pada bagian ini juga dipaparkan tentang indentifikasi etnik di Indonesia dan perkembangan etnisitas dalam sejarah bangsa.
Keseluruhan karya tulis ini dibuat dengan mengolah kepustakaan secara rasional dan argumentatif. Penulisan tidak mengadopsi secara keseluruhan dari konsep yang ditawarkan oleh beberapa ahli tetapi lebih pada penjabaran dan pemahaman konsep. Dari informasi yang diperoleh dinyatakan bahwa keberadaan etnosentrisme selalu menghalangi pemberdayaan civil society. Namun ada juga yang menyatakan bahwa etnosentrisme tidak menghalangi pemberdayaan bila dilihat dari implikasi etnisitas. Konsep ini kemudian dianalisa secara rasional dan disimpulkan dalam pernyataan bahwa etnosentrisme tidak selalu menghalangi pemberdayaan civil society tetapi dapat pula mengembangkan civil society itu sendiri.
Kaitan pemberdayaan civil society dalam acuannya dengan wacana etnisitas dijelaskan dalam beberapa hal. Pertama, civil society dan etnisitas dalam sejarah bangsa Indonesia, menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah bangsa indonesia yang mencerminkan adanya pemberdayaan civil society dengan mengacu kepada kesamaan visi dan misi di tengah kompleksitas budaya dan suku bangsa. Kedua, etnosentrisme bukan kendala pembentukan civil society, yang menjelaskan tentang keberadaan etnosentrisme bukan hanya menjadi kendala dalam perjuangan dan pemberdayaan civil society. Dan ketiga, bagaimana arah dan prospek civil society dilatarbelakangi oleh adanya aplikasi dari wacana etnisitas ini.
Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa etnisitas dapat menjadi solusi dalam pemberdayaan civil society. Konsep etnisitas ini berlaku ketika bangsa Indonesia menyadari dirinya sebagai satu kesatuan yang digeneralisasikan dalam wacana sebagai etnik Indonesia. Pada bagian ini juga dipaparkan beberapa saran teoritis dan praktis untuk menggenapi wacana pemberdayaan civil society dalam konteks etnisitas sebagai satu solusi dalam peningkatan daya saing bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Pemberdayaan masyarakat Indonesia yang mengacu kepada civil society merupakan sebuah gerakan yang saat ini menjadi salah satu wacana dalam pembangunan bangsa menuju peradaban rakyat. Di sini bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa dan budaya merupakan satu tantangan tersendiri dalam pemberdayaan civil society. Namun hal itu bukanlah satu tantangan berarti ketika ada kesatuan persepsi yang terangkum dalam satu pandangan sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut yang melatar belakangi penulisan ini. Pembahasan ini bertujuan untuk melengkapi strategi pemberdayaan civil society yang sudah diaplikasikan dan memberikan satu dasar pemberdayaan yang lebih kultural sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di era perkembangan global dewasa ini.
Tendensi konseptual perihal konsep civil society dan etnisitas ini, dijelaskan oleh beberapa ahli dari luar dan kaum intelektual Indonesia yang memiliki perhatian pada masalah pemberdayaan civil society. Bagian ini menjabarkan terminologi civil society. Dijelaskan juga kharakteristik, esensi, dan tantangan-tantangan dalam pemberdayaan civil society itu sendiri. Dalam kerangka pembahasan konsep, wacana etnisitas jabarkan sebagai sebuah konsep yang lebih mengacu pada teori Webber. Pada bagian ini juga dipaparkan tentang indentifikasi etnik di Indonesia dan perkembangan etnisitas dalam sejarah bangsa.
Keseluruhan karya tulis ini dibuat dengan mengolah kepustakaan secara rasional dan argumentatif. Penulisan tidak mengadopsi secara keseluruhan dari konsep yang ditawarkan oleh beberapa ahli tetapi lebih pada penjabaran dan pemahaman konsep. Dari informasi yang diperoleh dinyatakan bahwa keberadaan etnosentrisme selalu menghalangi pemberdayaan civil society. Namun ada juga yang menyatakan bahwa etnosentrisme tidak menghalangi pemberdayaan bila dilihat dari implikasi etnisitas. Konsep ini kemudian dianalisa secara rasional dan disimpulkan dalam pernyataan bahwa etnosentrisme tidak selalu menghalangi pemberdayaan civil society tetapi dapat pula mengembangkan civil society itu sendiri.
Kaitan pemberdayaan civil society dalam acuannya dengan wacana etnisitas dijelaskan dalam beberapa hal. Pertama, civil society dan etnisitas dalam sejarah bangsa Indonesia, menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah bangsa indonesia yang mencerminkan adanya pemberdayaan civil society dengan mengacu kepada kesamaan visi dan misi di tengah kompleksitas budaya dan suku bangsa. Kedua, etnosentrisme bukan kendala pembentukan civil society, yang menjelaskan tentang keberadaan etnosentrisme bukan hanya menjadi kendala dalam perjuangan dan pemberdayaan civil society. Dan ketiga, bagaimana arah dan prospek civil society dilatarbelakangi oleh adanya aplikasi dari wacana etnisitas ini.
Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa etnisitas dapat menjadi solusi dalam pemberdayaan civil society. Konsep etnisitas ini berlaku ketika bangsa Indonesia menyadari dirinya sebagai satu kesatuan yang digeneralisasikan dalam wacana sebagai etnik Indonesia. Pada bagian ini juga dipaparkan beberapa saran teoritis dan praktis untuk menggenapi wacana pemberdayaan civil society dalam konteks etnisitas sebagai satu solusi dalam peningkatan daya saing bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kita pantas berangkat dari sebuah sejarah. Sejarah bangsa Indonesia telah banyak melukiskan berbagai kenyataan dan pengalaman yang bisa menghadirkan sebuah kedewasaan bangsa. Sejak gerakan reformasi digulirkan, wacana tentang perubahan bangsa mulai dikampanyekan. Satu hal yang menjadi wacana publik adalah civil society (dalam keseluruhan karya tulis ini penulis menggunakan istilah civil society ketimbang istilah lain yang sampai sekarang masih berada dalam perdebatan konsep). Pemikiran ke arah civil society semakin gencar digelar dan dapat disimpulkan bahwa ini lahir dari semacam frustasi sosial akibat tekanan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak dengan rakyat.
Terlepas dari persoalan ini kita mungkin bisa menyimak, mengingat, bahkan mengalami sendiri sebagai rakyat apa yang terjadi saat ini. Mungkin pemerintah benar dengan UU otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan peran tendensial yang memungkinkan adanya kekuatan rakyat untuk berperan sendiri dalam mensejahterakan hidupnya. Namun kenyatan berbicara lain. Pilkada di daerah rusuh, korupsi di daerah, pencabutan hak sebagai gubernur, pemecatan terhadap anggota DPRD tanpa mengacu pada konstitusi, pemberontakan laten terhadap kelompok tertentu dan lain sebagainya telah menjadi berita di hampir semua channell televisi dan mass media lainnya.
Wacana di atas mungkin bisa memberikan satu gambaran tentang bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saat ini ketika demokrasi diagungkan, kebebasan sebagai rakyat mulai dimanfaatkan. Kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat akhirnya menjadi sebuah pergerakan yang menunjukkan identitas sebagai “rakyat”. Banyak kelompok yang terbentuk, entah itu kelompok etnik maupun kelompok massa lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu berada dalam sebuah kendali, cita-cita, dimana tatanan nilai yang diperjuangkan berdasarkan budaya sendiri bahkan akhirnya membentuk sebuah kekuatan frontal yang mengagungkan kelompoknya sendiri.
Kita boleh percaya dan boleh tidak akan adanya kemerosotan moral humanistik yang kini menampilkan dirinya. Melihat gejala ethnic cleaning, genocide di Rwanda, Yugoslavia, Kongo-Zaire, Kamboja, Ambon, Poso, Aceh dan lain-lain, maka kesadaran dan kepastian kita akan daya kekuatan iman dan rasio diguncang keras. Bila kita merefleksikan kenyataan ini bisa kita lihat bahwa kejahatan terhadap jati diri bangsa telah merajalela. Hal ini akhirnya memberikan satu panorama baru bahwa kejahatan menjadi roh baru yang bergerak dan berusaha mencabut peradaban manusia. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kemanusiaan kita sebagai sebuah bangsa.
Tragedi Ambon, Poso, Aceh terjadi beradasarkan hal-hal tragis bisa saja terjadi kembali tetapi peristiwa-peristiwa tersebut terlalu cepat berlalu dan terlupakan. Namun perlu disadari bahwa kita ditegur untuk terpaksa bertanya tentang motor penggerak kemanusiaan kita. Di sini juga realitas jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan demokratis dipertanyakan. Hakikat keberadaban pun secara sementara pantas berada dalam sebuah kerangka utopia.
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar terkadang bisa menghancurkan kesatuan bangsa ini. Keragaman budaya yang telah dipersatukan dalam kompleksitas kebudayaan nasional bukan tidak mungkin telah menjadi bagian yang sulit bahkan menjadi tantangan dalam pembentukan civil society. Etnosentrisme, primordialisme, rasisme bahkan menjadikan segenap rakyat Indonesia berpola pikir sempit dan tidak mau peduli dengan bangsanya sendiri.
Perwujudan sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa memang sejak tahun 1928 telah dikumandangkan. Bahkan sebelum itu, ketika era kebangkitan bangsa bergulir, hakikat sebagai satu bangsa menjadi landasan perjuangan para pahlawan intelektual masa itu. Memang hal ini bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sengketa atau konflik dalam kenyataan sehari-hari yang terjadi didasarkan oleh adanya prasangka budaya dan keagungan primordialisme yang membentuk sebuah aliran etnosentris yang negatif (sebuah aliran yang non-univesality).
Mengkaji akan banyaknya keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia maka dihadirkan sebuah wacana sebagai pemecahan masalah yang menjadi tolok ukur dalam pemberdayaan civil socety. Bukanlah hal yang mustahil pemberdayaan civil society dibangun dari adanya kesatuan konsep budaya, yang menunjukkan bahwa ini bukan ras tertentu atau etnik tertentu tetapi segenap bangsa Indonesia yang menghadirkan sebuah label sebagai satu etnik bangsa atau satu ras atau satu suku yakni Indonesia. Konsep ini bukanlah sebuah konsep baru tetapi hanya merupakan iktisar dari wacana tentang kebudayaan nasional, kebudayaan yang merupakan rangkuman dari kebudayaan daerah dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Keragaman budaya Indonesia dimanifestasikan dalam keragaman pola pikir dan perilaku masyarakat. Masing-masing manusia Indonesia memang berbeda. Namun perbedaan itu bisa disatukan dalam sebuah konteks rasa, pola pikir, dan perilaku sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang berkembang di Indonesia memberikan andil untuk perumusan kesamaan persepsi sebagai bangsa. Kajian demokratisasi yang bertolok ukur dari pemberdayaan masyarakat yang beradab memang berjalan sesuai dengan frame yang ada. Namun terkadang para pelaku demokrasi termasuk rakyat sendiri melupakan sebuah identitas bangsa bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa.
Rakyat Indonesia masih sulit melepaskan tradisi kesukuan di atas pamor primordialisme dan etnosentrisme yang sempit. Logikanya ketika tradisi itu diagungkan maka keangkuhan identitas suatu suku menjadi awal malapetaka sengketa nasional entah itu secara laten maupun terbuka. Ketika keragaman ini ada, adalah sangat benar wakil rakyat mengeluarkan UU otonomi daerah. Akan tetapi kita patut bertanya sudah relevankah keadaan ini dengan struktur sosial kemasyarakatan yang ada ?
Pembentukan civil society dimanifestasikan dalam sebuah aktivitas dan partisipasi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Di sini masyarakat dapat dikatakan beradab. Namun terkadang keadaan ini malah menghancurkan masyarakat itu sendiri. Generalisasi ini bukannya tanpa fakta. Sterotype dan prasangka masing-masing etnik atau suku atau ras bisa menciptakan chaos.
Kenyataan yang dipaparkan di atas memang bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi bagi penulis ini adalah sebuah permasalahan yang faktual sepanjang masa sebelum bangsa ini merasa, berpikir, dan berperilaku sebagai satu bangsa. Memang ini sangat sulit ketika pemberdayaan civil society dibentengi oleh sebuah tradisi kesukuan antar satu dengan yang lainnya. Banyak diskusi dan diskursus yang dilakukan untuk mengangkat permasalahan ini. Namun solusinya masih hanya pada sebuah konsep walaupun kalau dikaji secara konseptual wacana ini sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan.
Akan tetapi itu semua bukanlah sebuah ‘sad ending’. Pergerakan demokrasi yang dilabeli oleh pemberdayaan civil society masih berada dalam sebuah usaha ke arah pemberdayaan dan pertumbuhan. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat kembali sebuah tema klasik yakni pemberdayaan civil society yang dipertemukan oleh kesatuan bangsa dalam kerangka kebudayaan yang beragam ini. Etnosentrisme dan rasisme yang menjadi tantangan dalam sebuah pemberdayaan civil society bisa dihindari. Konsep etnosentrisme dan rasisme bukanlah sesuatu yang negatif, mengandaikan bangsa ini memahami benar apa itu sebuah kesatuan bangsa. Dalam hal ini kesatuan pandangan budaya sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dalam wacana etnisitas nasional.
Ini bukanlah sesuatu yang mustahil yang menghadirkan keberadaan konsep sebagai sebuah bangsa di antara beribu bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Pemberdayaan civil society dalam kesadaran etnik sebagai satu bangsa akan meningkatkan daya juang bangsa ini. Wacana etnisitas yang terlepas dari etnosentrisme sempit memberikan prospek dan arah pada pemberdayaan peradaban manusia Indonesia dalam meningkatkan peran serta untuk berkompetisi secara sehat menanggapi perkembangan global dengan negara lain.
1.2 Uraian Pembahasan
Wacana civil society bukanlah sesuatu yang baru. Demikian juga konsep etnisitas. Kedua hal ini saling berkaitan. Dimensi keragaman bangsa Indonesia merupakan tolok ukur dari keseluruhan pembahasan ini. Civil society merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi yang menjamin peradaban sebagai bangsa. Sedangkan etnisitas merupakan kesatuan pandangan sebagai suatu etnik yakni bangsa Indonesia. Karya tulis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I membahas tentang latar belakang masalah yang juga merangkum perumusan masalah, uraian singkat pembahasan, manfaat dan tujuan penulisan ini. Bab II, penulis membahas tendensi konseptual yang mengejawantahkan pemaparan teori, pandangan para tokoh, dan proses pemecahan masalah civil socitey yang pernah dilakukan. Bab III, dipaparkan metode penulisan, perihal bagaimana penulis melakukan penulisan ini sampai dengan kesimpulan akhir. Pada bab IV, penulis menjabarkan pembahasan menyangkut kaitan antara paparan teoritis yang sudah dijelaskan. Pada bab V penulis menyampaikan kesimpulan dan saran untuk implementasi wacana yang ditawarkan di sini.
1.3 Tujuan Penulisan
Karya tulis ini ditulis untuk memenuhi perlombaan karya tulis mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Akademik Ditjen Dikti Depdiknas. Karya tulis ini juga ditujukan untuk memaparkan konsep etnisitas yang kurang dikembangkan sebagai satu wacana yang bisa menumbuhkan kesadaran dalam pembentukan dan pemberdayaan civil society. Karya tulis ini berusaha untuk mendeskripsikan bahwa etnosentrisme tidak selalu menghalangi sebuah peradaban bangsa jika adanya kesadaran dalam wacana satu budaya sebagai bangsa Indonesia.
1.4 Manfaat Penulisan
Konsep yang ditulis dan ditawarkan dalam karya tulis ini dapat berfaedah dalam pembinaan kesadaran demokratis bangsa sehingga pemberdayaan dan perkembangan sebagai sebuah bangsa dapat digalangkan. Penulisan ini juga dapat dimanfatkan untuk bahan dalam kampanye atau diskursus atau dialog pemberdayaan civil society yang sampai sekarang masih dilakukan. Penulisan ini juga sekaligus untuk membantu kesadaran publik bangsa dalam wacana etnisitas sebagai tendensi dalam pemberdayaan civil society untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Kita pantas berangkat dari sebuah sejarah. Sejarah bangsa Indonesia telah banyak melukiskan berbagai kenyataan dan pengalaman yang bisa menghadirkan sebuah kedewasaan bangsa. Sejak gerakan reformasi digulirkan, wacana tentang perubahan bangsa mulai dikampanyekan. Satu hal yang menjadi wacana publik adalah civil society (dalam keseluruhan karya tulis ini penulis menggunakan istilah civil society ketimbang istilah lain yang sampai sekarang masih berada dalam perdebatan konsep). Pemikiran ke arah civil society semakin gencar digelar dan dapat disimpulkan bahwa ini lahir dari semacam frustasi sosial akibat tekanan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak dengan rakyat.
Terlepas dari persoalan ini kita mungkin bisa menyimak, mengingat, bahkan mengalami sendiri sebagai rakyat apa yang terjadi saat ini. Mungkin pemerintah benar dengan UU otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan peran tendensial yang memungkinkan adanya kekuatan rakyat untuk berperan sendiri dalam mensejahterakan hidupnya. Namun kenyatan berbicara lain. Pilkada di daerah rusuh, korupsi di daerah, pencabutan hak sebagai gubernur, pemecatan terhadap anggota DPRD tanpa mengacu pada konstitusi, pemberontakan laten terhadap kelompok tertentu dan lain sebagainya telah menjadi berita di hampir semua channell televisi dan mass media lainnya.
Wacana di atas mungkin bisa memberikan satu gambaran tentang bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saat ini ketika demokrasi diagungkan, kebebasan sebagai rakyat mulai dimanfaatkan. Kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat akhirnya menjadi sebuah pergerakan yang menunjukkan identitas sebagai “rakyat”. Banyak kelompok yang terbentuk, entah itu kelompok etnik maupun kelompok massa lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu berada dalam sebuah kendali, cita-cita, dimana tatanan nilai yang diperjuangkan berdasarkan budaya sendiri bahkan akhirnya membentuk sebuah kekuatan frontal yang mengagungkan kelompoknya sendiri.
Kita boleh percaya dan boleh tidak akan adanya kemerosotan moral humanistik yang kini menampilkan dirinya. Melihat gejala ethnic cleaning, genocide di Rwanda, Yugoslavia, Kongo-Zaire, Kamboja, Ambon, Poso, Aceh dan lain-lain, maka kesadaran dan kepastian kita akan daya kekuatan iman dan rasio diguncang keras. Bila kita merefleksikan kenyataan ini bisa kita lihat bahwa kejahatan terhadap jati diri bangsa telah merajalela. Hal ini akhirnya memberikan satu panorama baru bahwa kejahatan menjadi roh baru yang bergerak dan berusaha mencabut peradaban manusia. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kemanusiaan kita sebagai sebuah bangsa.
Tragedi Ambon, Poso, Aceh terjadi beradasarkan hal-hal tragis bisa saja terjadi kembali tetapi peristiwa-peristiwa tersebut terlalu cepat berlalu dan terlupakan. Namun perlu disadari bahwa kita ditegur untuk terpaksa bertanya tentang motor penggerak kemanusiaan kita. Di sini juga realitas jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan demokratis dipertanyakan. Hakikat keberadaban pun secara sementara pantas berada dalam sebuah kerangka utopia.
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar terkadang bisa menghancurkan kesatuan bangsa ini. Keragaman budaya yang telah dipersatukan dalam kompleksitas kebudayaan nasional bukan tidak mungkin telah menjadi bagian yang sulit bahkan menjadi tantangan dalam pembentukan civil society. Etnosentrisme, primordialisme, rasisme bahkan menjadikan segenap rakyat Indonesia berpola pikir sempit dan tidak mau peduli dengan bangsanya sendiri.
Perwujudan sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa memang sejak tahun 1928 telah dikumandangkan. Bahkan sebelum itu, ketika era kebangkitan bangsa bergulir, hakikat sebagai satu bangsa menjadi landasan perjuangan para pahlawan intelektual masa itu. Memang hal ini bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sengketa atau konflik dalam kenyataan sehari-hari yang terjadi didasarkan oleh adanya prasangka budaya dan keagungan primordialisme yang membentuk sebuah aliran etnosentris yang negatif (sebuah aliran yang non-univesality).
Mengkaji akan banyaknya keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia maka dihadirkan sebuah wacana sebagai pemecahan masalah yang menjadi tolok ukur dalam pemberdayaan civil socety. Bukanlah hal yang mustahil pemberdayaan civil society dibangun dari adanya kesatuan konsep budaya, yang menunjukkan bahwa ini bukan ras tertentu atau etnik tertentu tetapi segenap bangsa Indonesia yang menghadirkan sebuah label sebagai satu etnik bangsa atau satu ras atau satu suku yakni Indonesia. Konsep ini bukanlah sebuah konsep baru tetapi hanya merupakan iktisar dari wacana tentang kebudayaan nasional, kebudayaan yang merupakan rangkuman dari kebudayaan daerah dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Keragaman budaya Indonesia dimanifestasikan dalam keragaman pola pikir dan perilaku masyarakat. Masing-masing manusia Indonesia memang berbeda. Namun perbedaan itu bisa disatukan dalam sebuah konteks rasa, pola pikir, dan perilaku sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang berkembang di Indonesia memberikan andil untuk perumusan kesamaan persepsi sebagai bangsa. Kajian demokratisasi yang bertolok ukur dari pemberdayaan masyarakat yang beradab memang berjalan sesuai dengan frame yang ada. Namun terkadang para pelaku demokrasi termasuk rakyat sendiri melupakan sebuah identitas bangsa bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa.
Rakyat Indonesia masih sulit melepaskan tradisi kesukuan di atas pamor primordialisme dan etnosentrisme yang sempit. Logikanya ketika tradisi itu diagungkan maka keangkuhan identitas suatu suku menjadi awal malapetaka sengketa nasional entah itu secara laten maupun terbuka. Ketika keragaman ini ada, adalah sangat benar wakil rakyat mengeluarkan UU otonomi daerah. Akan tetapi kita patut bertanya sudah relevankah keadaan ini dengan struktur sosial kemasyarakatan yang ada ?
Pembentukan civil society dimanifestasikan dalam sebuah aktivitas dan partisipasi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Di sini masyarakat dapat dikatakan beradab. Namun terkadang keadaan ini malah menghancurkan masyarakat itu sendiri. Generalisasi ini bukannya tanpa fakta. Sterotype dan prasangka masing-masing etnik atau suku atau ras bisa menciptakan chaos.
Kenyataan yang dipaparkan di atas memang bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi bagi penulis ini adalah sebuah permasalahan yang faktual sepanjang masa sebelum bangsa ini merasa, berpikir, dan berperilaku sebagai satu bangsa. Memang ini sangat sulit ketika pemberdayaan civil society dibentengi oleh sebuah tradisi kesukuan antar satu dengan yang lainnya. Banyak diskusi dan diskursus yang dilakukan untuk mengangkat permasalahan ini. Namun solusinya masih hanya pada sebuah konsep walaupun kalau dikaji secara konseptual wacana ini sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan.
Akan tetapi itu semua bukanlah sebuah ‘sad ending’. Pergerakan demokrasi yang dilabeli oleh pemberdayaan civil society masih berada dalam sebuah usaha ke arah pemberdayaan dan pertumbuhan. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat kembali sebuah tema klasik yakni pemberdayaan civil society yang dipertemukan oleh kesatuan bangsa dalam kerangka kebudayaan yang beragam ini. Etnosentrisme dan rasisme yang menjadi tantangan dalam sebuah pemberdayaan civil society bisa dihindari. Konsep etnosentrisme dan rasisme bukanlah sesuatu yang negatif, mengandaikan bangsa ini memahami benar apa itu sebuah kesatuan bangsa. Dalam hal ini kesatuan pandangan budaya sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dalam wacana etnisitas nasional.
Ini bukanlah sesuatu yang mustahil yang menghadirkan keberadaan konsep sebagai sebuah bangsa di antara beribu bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Pemberdayaan civil society dalam kesadaran etnik sebagai satu bangsa akan meningkatkan daya juang bangsa ini. Wacana etnisitas yang terlepas dari etnosentrisme sempit memberikan prospek dan arah pada pemberdayaan peradaban manusia Indonesia dalam meningkatkan peran serta untuk berkompetisi secara sehat menanggapi perkembangan global dengan negara lain.
1.2 Uraian Pembahasan
Wacana civil society bukanlah sesuatu yang baru. Demikian juga konsep etnisitas. Kedua hal ini saling berkaitan. Dimensi keragaman bangsa Indonesia merupakan tolok ukur dari keseluruhan pembahasan ini. Civil society merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi yang menjamin peradaban sebagai bangsa. Sedangkan etnisitas merupakan kesatuan pandangan sebagai suatu etnik yakni bangsa Indonesia. Karya tulis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I membahas tentang latar belakang masalah yang juga merangkum perumusan masalah, uraian singkat pembahasan, manfaat dan tujuan penulisan ini. Bab II, penulis membahas tendensi konseptual yang mengejawantahkan pemaparan teori, pandangan para tokoh, dan proses pemecahan masalah civil socitey yang pernah dilakukan. Bab III, dipaparkan metode penulisan, perihal bagaimana penulis melakukan penulisan ini sampai dengan kesimpulan akhir. Pada bab IV, penulis menjabarkan pembahasan menyangkut kaitan antara paparan teoritis yang sudah dijelaskan. Pada bab V penulis menyampaikan kesimpulan dan saran untuk implementasi wacana yang ditawarkan di sini.
1.3 Tujuan Penulisan
Karya tulis ini ditulis untuk memenuhi perlombaan karya tulis mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Akademik Ditjen Dikti Depdiknas. Karya tulis ini juga ditujukan untuk memaparkan konsep etnisitas yang kurang dikembangkan sebagai satu wacana yang bisa menumbuhkan kesadaran dalam pembentukan dan pemberdayaan civil society. Karya tulis ini berusaha untuk mendeskripsikan bahwa etnosentrisme tidak selalu menghalangi sebuah peradaban bangsa jika adanya kesadaran dalam wacana satu budaya sebagai bangsa Indonesia.
1.4 Manfaat Penulisan
Konsep yang ditulis dan ditawarkan dalam karya tulis ini dapat berfaedah dalam pembinaan kesadaran demokratis bangsa sehingga pemberdayaan dan perkembangan sebagai sebuah bangsa dapat digalangkan. Penulisan ini juga dapat dimanfatkan untuk bahan dalam kampanye atau diskursus atau dialog pemberdayaan civil society yang sampai sekarang masih dilakukan. Penulisan ini juga sekaligus untuk membantu kesadaran publik bangsa dalam wacana etnisitas sebagai tendensi dalam pemberdayaan civil society untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
BAB II
TELAAH PUSTAKA
TELAAH PUSTAKA
2.1 Civil Society
2.1.1 Terminologi Civil Society
Kata civil society sebenarnya berasal dari konsep Yunani yakni koinia politika yang menjelaskan sebuah komunitas politik dimana warga citizen terlibat langsung dengan pemerintahan polis. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society ialah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani Kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civility (kewargaan) dan urbanity (budaya kota), maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan (Hikam, 1999).
Terlepas dari akar kata di atas, Adam Ferguson memahami civil society sebagai sebuah visi etis dalam sebuah solidaritas sosial. Demikian juga Hegel mendefenisikan civil society sebagai sebuah lembaga sosial yang berada di antara keluarga dan negara, yang dipergunakan oleh warga sebagai ruang untuk mencapai pemuasaan kepentingan individu dan kelompok. Alexis de Tocqueville menyatakan civil society dapat dimengerti sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dalam ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara. Tocqueville juga menekankan di sini adanya dimensi kultural yang membuat civil society dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang, yakni semacam keterikatan dan kepatuhan terhadap norma-norma dan tradisi yang ditanamkan dalam masyarakat tertentu (Hikam, 1999).
Hefner (1998) menyatakan bahwa civil society merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan, dan perbedaan.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa civil society merupakan suatu kehidupan sosial yang menjamin kesinambungan interaksi dan solidaritas sosial yang dilandasi oleh keberadaan kultur atau tradisi atau norma dalam masyarakat tersebut. Di sini pluralitas dalam suatu masyarakat memberikan satu kebebasan dalam partisipasinya terhadap suatu kondisi global untuk menjamin sebuah peradaban.
2.1.2 Esensi, Kharakteristik Civil Society
Munculnya eksperimen demokrasi melalui pemberdayaan civil society setidaknya perlu dipahami esensi dari makna civil society itu sendiri. Hikam (1999) memaparkan beberapa esensi makna civil society, sebagai berikut :
1. Adanya individu dan kelompok mandiri dalam masyarakat. Kemandirian itu diukur terutama mereka berhadapan dengan negara
2. Adanya ruang publik bebas sebagai tempat wahana dan kiprah politik bagi warga negara
3. Kemampuan masyarakat dalam mengimbangi kekuatan negara, kendati tidak melenyapkannya secara total
Esensi ini kemudian dilengkapi oleh Bahmueller (dalam Suharto, 2002) yang mengemukakan, ada beberapa kharakteristik civil society, di antaranya:
1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif
3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat
4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah
5. Tumbuh kembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter
6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif
2.1.3 Tantangan Civil society
DuBois dan Milley (dalam Suharto, 2002) mengemukakan ada beberapa tantangan dalam civil society. Tantangan-tantangan tersebut hendaknya menjadi sebuah kewaspadaan dalam terbentuknya civil society yang berkesinambungan. Tantangan-tantangan tersebut dapat dideskripsikan seperti di bawah ini.
2.1.3.1 Sentralisme versus Lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam paham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme dan keadilan sosial.
2.1.3.2 Pluralisme versus Rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan dibandingkan dengan upaya untuk mengeliminasi kharakter etnis, pluralisme budaya, dan berjuang untuk memelihara integritas budaya.
Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.
2.1.3.3 Elitisme versus komunalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Sementara itu komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan.
2.2 Etnisitas : Sebuah Konsep
2.2.1 Etnosentrisme, Primordialisme dalam Wacana Etnisitas
Webber (dalam Mitakda,2000) membedakan antara etnik group dari ethnic membership. Grup etnik adalah kelompok yang terikat oleh kesamaan turunan, sosok fisik, adat istiadat, ataupun suatu memori atas penjajahan dan migrasi. Pertalian darah bagi Webber tidak terlalu mendasar untuk merekatkan tali ikat kelompok etnik. Tanpa hubungan darah kelompok etnik bisa terbentuk. Juga tindakan-tindakan sosial yang nyata tidak sekaligus menciptakan dan menciri khaskan grup etnik ini. Hal ini berbeda dengan corak etnik lain yakni keanggotaan etnik (ethnic membership) yang hanya memberikan peluang untuk mengorbankan kelompok saja khususnya kelompok partai. Ciri utamanya adalah komunitas politik. Webber tidak menggubris soal cara membentuk dan bentuk komunitas politik ini. Tulis Webber
Nyata bahwa kesadaran atau kesukuan tidak dibentuk untuk pertama-tama oleh pertalian leluhur yang sama, tetapi justru oleh pengalaman-pengalaman politik. Hal ini kini tampak telah menjadi sumber keyakinan yang menetap dalam suku pada umumnya
Webber menggarisbawahi kombinasi corak subyektif dan obyektif dari etnisitas. Webber memang berayun di antara dua kutub yang membentuk suatu kelompok etnik. Baginya naluri pemersatu kelompok etnik itu diayun oleh faktor-faktor politis dan peristiwa masa lampau tetapi sekaligus juga oleh kesatuan budaya dengan perbedaan-perbedaan biologis yang sekaligus memberikan batas afiliasi etnik. Dalam konteks ini bahasa menjadi penting. Bahasa bukan saja dipandang sebagai satu perekat kuat dari kelompok etnik dan keanggotaan kelompok etnik. Bahasa juga adalah pembawa dan pemelihara kepemilikan budaya yang khusus dari kelompok yang menyebabkan sikap saling memahami menjadi mungkin dan mudah. Hilang dan lemahnya salah satu faktor akan mengancam daya kekuatan etnik bahkan menyebabkan satu etnik hilang dari muka bumi. Tentang daya kekuatan etnik ditentukan oleh beberapa faktor. Webber menulis
…..mengambil bagian dalam memori politik, atau bahkan lebih penting lagi pada masa-masa awal dimana ada tautan erat dengan kultur lama ataupun juga pemberdayaan pertalian keluarga dan kelompok lain baik dalam komunitas yang baru maupun tua atau hubungan-hubungan lain yang masih bertahan (Mitakda, 2000).
Salah satu unsur pengendapan dari analisis Webber tentang asal-usul kelompok etnik adalah corak pasifitas individu dibentuk oleh suatu daya di luar dirinya sendiri. Pandangan ini mengingatkan kita akan concience collective-nya Emille Durkheim. Tali pertautan yang mengikat kelompok etnik ini disebut oleh Clifford Gerth dengan istilah keterlekatan primordial. Dengan ikatan Primordial menunjukkan ada suatu ikatan yang diberi tanpa dikehendaki sang individu. Individu adalah bagian darinya. Individu justru lahir dalam komunitas yang partikular dimana dia berbicara dari dialek yang bersangkutan dan mengikuti adat istiadat setempat (Mitakda, 2000).
Apa yang masyarakat rasa sebagai pantas dan bernilai dan tidak bisa ditelusuri kembali ke keputusan individu atau preferensi. Tidak seorangpun dapat memutuskan secara otonom sesuatu yang bernilai atau tidak. Penghargaan kita tidak dapat diciptakan atau dibuat, tetapi tergantung pada sesuatu yang melampaui kemampuan individu. Ikatan primordial adalah hadiah kebudayaan bagi seorang individu yang sifatnya tidak terlukiskan. Di dalam lingkungan ini dia merasa lebih aman pun dalam semua ketidak pastian perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ikatan ini lebih semata-mata tautan natural.
Masih banyak konsepsi tentang etnisitas yang dibicarakan filsuf-filsuf dan antropolog sosial tetapi di sini hanya mengacu pada beberapa pembatasan. Enam corak dalam kelompok etnik (Mitakda, 2000) yakni :
1. Satu nama diri yang umum untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan esensi dari komunitas atau grup tersebut
2. Suatu fakta tentang permoyangan, leluhur yang lebih dari sekedar fakta yakni suatu mitos yang mengandung ide tentang asal-usul bersama.
3. Ada unsur yang turut ambil bagian dalam memori-memori masa lampau
4. Memiliki satu atau lebih unsur-unsur budaya yang sama yang tidak selalu diklasifikasikan dalam agama, adat istiadat, dan bahasa
5. Ada suatu tautan dengan tanah air
6. Ada suatu rasa solidaritas pada kelompoknya
Keseluruhan etnosentrisme dan primordialisme ini mengacu kepada satu konsep yakni etnisitas. Etnisitas dibedakan dari ras, yang menekankan perbedaan biologis yang dicirikan oleh warna kulit. Etnisitas mengartikan suatu cita rasa dalam mana seorang termasuk dalam suatu komunitas khusus yang anggota-anggotanya memiliki tradisi yang sama. Tradisi mencakup semua makna simbolik seperti seni, agama, bahasa, dan komponen budaya lainnya. Harus ditekankan di sini bahwa fenomena etnisitas ini tidak identik dengan ras dan etnosentrisme. Etnisitas lebih mengacu kepada sebuah kekuatan dalam integritas, suatu keadaan yang menyatukan beragam komponen etnik dalam satu persepsi
2.2.2 Identifikasi Etnisitas di Indonesia
Bila mengkaji etnisitas di Indonesia berdasarkan kriteria linguistik, orang akan sampai pada jumlah kelompok etnis lebih dari 250, sedangkan apabila kita mengikuti kajian Van Vollehoven, hanya ada 18 lingkungan hukum adat. Sementara itu, kelompok etnis juga dapat digolongkan berdasarkan sistem kepercayaaan, adat- istiadat (folkways), sistem kekerabatan, dan sebagainya.
Eksistensi satuan-satuan etnis secara etnografis telah ada jauh sebelum zaman modern. Berdasarkan deskripsi kota Malaka pada sekitar tahun 1500 oleh Tome Pires, terdapat puluhan kelompok etnis seperti Aceh, Melayu, Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Ambon, dan sebagainya. Masing-masing mempunyai perkampungan sendiri, jelas-jelas menunjukan otonominya sebagai kesatuan. Masing-masing golongan etnis memiliki stuktur sosial dan sistem hukumnya sendiri, jadi merupakan komunitas terpisah satu sama lain, namun pada masa itu sudah ada komunikasi lewat navigasi dan bahasa Melayu. Banyak nama etnik sama dengan nama daerahnya, bahkan sekaligus menunjukan nama kebudayaannya. Pada masa Majapahit ada banyak nama daerah (termasuk etniknya), tetapi kultur politiknya belum mencakupinya sebagai satu kesatuan. Seperti telah diketahui, hegemoni Majapahit mewujudkan struktur hirarki sehingga antar sub stuktur tidak banyak terjadi interaksi langsung kecuali komersial (Kartodirjo, 1999).
Pada masa kekuasaan sentral mengalami dekadensi, timbul disintegrasi serta proliferasi kekuasaan, maka kemudian timbullah kerajaan-kerajaan regional atau “lokal”. Unit-unit sistem menonjol. Sebagai contoh adalah munculnya kerajaan-kerajaan muslim di pantai utara Jawa. Diferensiasi etnik tidak terjadi. Kekuatan sentrifugal dominan selama satu abad (1500-1600), baru kemudian muncul lagi kekuatan sentripetal yang mampu menciptakan integrasi regional seperti ekspansi Aceh, Riau, Jambi, Mataram, Banjarmasin, dan sebagainya (Kartodirjo, 1999).
2.3 Civil Society dan Etnosentrisme dalam Sejarah Indonesia
Menurut sejarah peradaban (civilization), etnosentrisme merupakan manuskrip yang universal, antara lain indosentrisme, sinosentrisme, javanosentrisme, dan sebagainya. Hubungan antar etnik memerlukan proses mentransendensi kebudayaan etnik satu sama lain. Kerangka yang mencakup dua atau lebih etnisitas bersifat meta etnik, hal yang baru kita dapati pada zaman modern, mulai dari masa kolonialisme abad ke 19.
Perjuangan civil society di Indonesia pada awal pergerakan kebangsaan dipelopori oleh Syarikat Islam (1912) dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan (Norlholt, 1999). Jiwa demokrasi Sultan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif baik dari rezim orde lama di bawah pimpinan Soekarno maupun rezim orde baru di bawah pimpinan Soeharto, tuntutan perjuangan transformasi menuju peradaban bangsa pada era reformasi ini tampaknya sudah tidak terbendungkan lagi.
Dalam memasuki milenium III, tuntutan akan masyarakat yang beradab di dalam negeri oleh kaum reformis yang anti status quo menjadi semakin besar. Civil society yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar (Nordholt, 1999), jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia (Farkan, 1999).
Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya civil society ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis. Selain itu menurut Daliman (1999), dengan terwujudnya civil society, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian "kue bangsa" antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antarwarga dan lain-lain yang selama orde baru lebih banyak ditutup-tutupi, direkayasa dan dicarikan kambing hitamnya; diharapkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah.
Guna mewujudkan civil society dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini mendukung pendapat Daliman (1999) yang intinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang beradab diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tidak terelakan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi.
Ciri utama civil society adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuensi luas di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan.
BAB III
METODE PENULISAN
METODE PENULISAN
3.1 Prosedur Pengumpulan Informasi
Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan dan men-download file di internet. Dalam proses ini penulis berusaha memilah dari berbagai macam teori tentang civil society dan etnisitas. Beragamnya teori yang ada menjadikan proses ini berjalan pada satu kerangka perbandingan untuk menentukan relevansi dengan wacana etnisitas dan civil society.
3.2 Pengolahan Informasi
Wacana civil society dan etnisitas diolah melalui proses penemuan konsep yang setimbang. Ketika menemukan kesetaraan dan keterkaitan antara dua variabel dalam penulisan ini, penulis mencoba menganalisa dan kemudian kembali menemukan insight yang membantu perumusan konsep. Dalam pengolahan data penulis juga sempat mengadakan diskusi untuk menemukan jalan tengah yang bisa menemukan kejelasan dalam konsep yang ingin ditulis ini. Dalam mengolah informasi ini, kerangka dalam konsep etnisitas dan civil society ini penulis lebih banyak mengandalkan rasionalisasi yang tetap berpatokan pada sumber informasi yang telah penulis dapatkan sekaligus juga penjabaran dari kenyataan yang didengar, dipahami, dan dialami oleh penulis.
3.4 Analisis –Sintesis
Civil society merupakan sebuah wacana yang tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur kehidupan rakyat. Salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan adalah budaya rakyat itu sendiri. Keberadaan budaya rakyat sangat mempengaruhi pemberdayaan civil society itu sendiri. Dengan analisa yang terstruktur dan terbuka penulis memaparkan konsep civil society dalam kaitannya dengan konsep budaya. Keberadaan budaya tidak terlepas dari satu kesatuan. Etnosentrisme yang umumnya diklaim sebagai sebagai tantangan integritas bangsa bukanlah sesuatu yang mutlak. Etnosentrime positif membuktikan ini dengan menekankan satu kesatuan konsep dalam wacana etnisitas yang menurut penulis dapat memperkuat integritas bangsa dalam praktek pemberdayaan civil society. Apabila etnisitas menjadi satu kesadaran dari semua komponen bangsa untuk membentuk kesatuan etnik, satu bangsa, yakni Indonesia, maka pemberdayaan peradaban bangsa bukanlah sebuah utopia.
3.5 Perumusan Simpulan dan Saran
Setelah mengkaji lebih jauh tentang pembahasan yang ada penulis menarik titik tengah yang mempertemukan kedua wacana ini, civil society dan etnisitas dan menjadikannya sebagai konsep yang lebih bermakna. Setelah penguraian ini maka penulis bisa merumuskan pemecahan masalah yang dipikir bisa membantu proses pemberdayaan civil society ini.
PEMBAHASAN
4.1 Civil Society vs Etnisitas dalam Sejarah Indonesia : Sebuah Perjalanan
Sudah disinyalir dan dipaparkan di depan (dalam landasan konseptual) keragaman bangsa Indonesia telah menjadikan bangsa ini besar. Sejak zaman dahulu perjuangan ke arah peradaban masyarakat bukan merupakan sebuah adopsi dari barat atau dari timur tengah. Pergerakan era kebangkitan bangsa yang dicetuskan oleh berdirinya Budi Utomo menjadi tonggak berdirinya sebuah paradigma kehidupan dalam wacana civil society. Sumpah pemuda 1928 akhirnya mempublisitaskannya dalam kancah pergerakan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kekuatan para pemuda di arena kebangkitan bangsa bukan dimotori oleh kesukuan yang sempit tetapi lebih digerakkan oleh kekuatan nasionalis yang menyuarakan persatuan dan kesatuan dalam kerangka berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu yakni Indonesia. Ini adalah sebuah implikasi dari keberadaan perjuangan kerajaan masa lalu dan mitos-mitos yang sudah mentradisi. Persatuan dan kesatuan dalam tatanan kerakyatan yang merdeka menyatupadukan sebuah kekuatan frontal untuk membentuk identitas sebagai bangsa.
Memang pembentukan identitas bangsa telah dipengaruhi oleh kolonialisme. Kolonialisme yang bertahun-tahun menggerayangi wajah Indonesia memberikan identitas baru dalam jiwa bangsa. Penanaman demokrasi yang pernah diterapkan hanya merupakan sebuah penjajahan. Kaum kolonial lupa bahwa kesatuan Hindia Belanda terbetuk dari keragaman dari suku dan bangsa.
Terlepas dari peran kolonialisme dalam pembentukan sebuah masyarakat, kita melihat jiwa yang berkembang di antara kaum cendikiawan pra kemerdekaan yang sangat mengupayakan persatuan. Lahirnya era Kebangkitan Bangsa telah menjadikan etnosentrime bukanlah etnosentrisme sempit yang mengupayakan keagungan pribadi rakyat Indonesia dalam identitas sebagai suku Jawa, atau Ambon, atau Flores, atau Batak, tetapi lebih sebagai satu kesatuan sebagai etnik Indonesia.
Perjalanan pembentukan civil society dalam kultur bangsa yang majemuk ini bukanlah sesuatu yang gampang. Konflik horizontal dan primordialisme yang bermula dari stereotype tetap membuahkan konflik yang secara beruntun terjadi sejak zaman pra kemerdekaan bahkan sampai sekarang.
Titik tolaknya adalah bahwa kesatuan bangsa ini belum didasarkan pada sebuah kesatuan perasaan dan pola pikir sebagai individu ber-etnik Indonesia. Ketiadaan persepsi ini sehingga dalam perjalanan sejarah bangsa, civil society masih merupakan sebuah konsep tanpa praksis, sebuah konsep yang masih berada dalam sebuah idealisme yang siap dicetuskan oleh kaum pintar atau cendekiawan yang punya intensi khusus untuk persoalan ini.
4.2 Etnosentrisme Bukan Kendala Pembentukan Civil Society
Etnosentrisme merupakan sebuah keterlibatan yang lebih berpihak pada sebuah suku bangsa tertentu. Keberpihakan pada suatu suku bangsa menjadikan bangsa ini terpecah belah. Namun yang dilihat di sini adalah etnosentrisitas yang memberdayakan. Keragaman suku bangsa dan budaya bukan sesuatu yang bisa menghancurkan peradaban tetapi malah membangun peradaban itu menjadi sebuah kekuatan yang lebih dinamis bila ditilik dari kacamata etnisitas sebagai bangsa Indonesia.
Keragaman itu harusnya tetap ada. Keragaman itu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa ini. Ketika mengurai syarat menuju sebuah masyarakat yang demokratis dan beradab (civil society) dapat disimpulkan adanya suatu masyarakat yang mandiri dan beradab. Ini bukanlah tidak mungkin ketika tradisi budaya diatur dalam sebuah skema tertentu yakni konstitusi. Memang ini akan mengundang banyak polemik. Di sinilah peran kekritisan para pelaku dan pembuat konstitusi mengenai budaya berperan besar.
Bangsa Indonesia yang plural tidak bisa diabaikan dari pemberdayaan civil society, yang memberikan landasan pemikiran sebuah peradaban. Letak akar pemberdayaan civil society berada dalam kerangka keragaman etnik Indonesia ini. Jadi bukanlah satu hal yang benar ketika ada yang mengacungkan tangan dan menyatakan bahwa etnosentrisme harus dihilangkan dalam pemberdayaan civil society. Etnosentrisme harus tetap ada. Di sini konsep etnisitas menjadi fondamen untuk mendongkrak sebuah pemurnian pandangan terhadap etnosentrisme yang lebih dinilai negatif. Bertolak dari ini mungkin pantas diwacanakan dan dideklarasikan sebuah konsep yakni etnik Indonesia.
4.3 Arah dan Prospek Civil Society dalam Wacana Etnisitas
Civil society merupakan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, pluralistis, transparan, dan partisipatif dimana peran infra dan supra struktur berada dalam keseimbangan yang dinamis. Berbagai perubahan–perubahan sosial politik yang cukup signifikan terjadi oleh sementara orang dipandang sebagai pendorong proses demokratisasi dan perkembangan civil society. Namun, sebagian pendapat mengatakan prospek masyarakat ini dalam tahun-tahun mendatang kelihatannya belum serba pasti. Ada perkembangan tertentu yang menggembirakan, kondusif, dan mendukung bagi pencipta civil society, tetapi pada saat yang sama ada juga perkembangan dan indikasi tertentu yang kurang menggembirakan yang pada gilirannya dapat menjadi tantangan bagi perkembangan peradaban masyarakat itu sendiri.
Di sini kita dapat melihat banyak terjadi pergeseran nilai sosial dan politik dalam tatanan masyarakat sebagai siklus perubahan dimana kita tengah berada pada titik memulai kembali pembentukan civil society dengan menyatukan kembali perbedaan-perbedaan menjadi sebuah pengakuan atas pluralitas yang stabil dan dinamis, yang di dalamnya masyarakat memiliki ruang untuk bernapas dengan komitmen kemanusiaan dan keadilan.
Akan tetapi harus diakui, membangun sebuah masyarakat yang berperadaban, maju dan bermartabat dalam ikatan persamaan dan persaudaraan sejati memerlukan kerangka dan pendekatan yang lebih bersifat evolusioner dari pada revolusioner. Dalam wacana pendekatan terhadap budaya memberikan arah yang frontal dan signifikan untuk membentuk sebuah pembaruan dalam pemberdayaan civil society. Adalah mustahil untuk menegakkan sebuah pluralitas yang berakar dari kesamaan dan persaudaraan sejati jika penghormatan pada martabat dan nilai kemanusiaan jika pendekatan sosio-kultur tidak pernah digalakkan.
Arah civil society yang dibangun dalam wacana etnisitas ini memberikan sebuah prospek tendesial dan fungsional dalam membentuk horisontalitas yang dinamis dan mengukuhkan sebuah masyarakat yang lebih berbudaya. Namun arah ini bukan memisahkan suku dan bangsa dalam sebuah dikotomi tetapi dijabarkan dalam sebuah kesatuan pandangan sebagai bangsa Indonesia.
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Etnisitas merupakan sebuah perangkat yang membentuk adanya kesatuan identitas sebagai individu berkelompok. Sejarah telah membuktikan bahwa peran perbedaan dalam budaya bukan menjadi halangan dalam menciptakan masyarakat peradaban. Civil society mengandaikan adanya satu kesepakatan nasional untuk menjamin demokratisasi rakyat yang lebih bertanggung jawab. Peradaban bangsa memang pantas dipertanyakan ketika kekuatan yang tercermin menggadaikan peradaban itu sendiri.
Keadaan Indonesia yang plural bukan mustahil akan menghalangi pemberdayaan civil society. Namun perlu diingat perbedaan ini akan menguatkan bangsa itu sendiri ketika masing-masing rakyat Indonesia memiliki satu paham dalam konteks etnisitas yang universal sebagai etnik Indonesia. Keberadaan sebagai etnis Indonesia ini sudah tentu akan menjamin sebuah kekuatan mental yang membantu peningkatan daya saing bangsa dalam menyikapi perkembangan global dewasa ini. Jika segenap komponen bangsa Indonesia berada dalam konteks sebagai sebuah kesatuan yang berbudaya yang sama, berbahasa yang sama, bertanah air yang sama maka pantas dikatakan bahwa civil society versus etnisitas bukanlah konsep utopia.
5.2 Saran
Mungkin mudah bila kita menempatkan wacana civil society dalam setiap kampanye-kampanye tentang demokrasi. Konsep etnisitas yang dipaparkan oleh penulis bukanlah konsep baru. Ini sudah ada sejak perjuangan pra kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hal yang dapat penulis paparkan sebagai saran :
1. Pembentukan kesadaran sebagai bangsa yang beragam dari segi budaya yang pada akhirnya bisa menimbang satu kesatuan yang memberikan kekuatan mental untuk tetap bersatu
2. Menciptakan satu keadaan yang tidak memutlakkan primordialisme dan etnosentrisme yang sempita sehingga pertentangan antar etnik ataupun antar kelompok massa dapat dengan mudah dihindarkan.
Beberapa catatan praktis yang bisa dipaparkan di sini :
1. Dialog berkesimbungan antara pemerintah dan elemen budaya seperti tetua adat dari suku terkecil sampai kelompok etnik modern
2. Pemerintah memberikan awasan kepada radikalisme kelompok yang sudah mengancam integritas bangsa
3. Tindakan keras kepada kelompok yang mengatasnamakan rakyat tetapi terlihat jelas hanya mementingkan kelompok dan idelisme kelompoknya sendiri.
4. Menjadikan wacana ini sebagai sebuah konsep yang bisa diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan demokrasi yang berkesinambungan. Hal ini membentuk akar yang kuat dalam sebuah perumusan civil society yang utuh. Namun wacana yang diajarkan hendaknya berdasarkan sebuah perumusan yang tepat sasar bukan adopsi dari pendidikan barat.
5. Amandemen konstitusi. Ini adalah sesuatu yang urgen dalam pembentukan sebuah keteraturan budaya, tradisi, yang akhirnya bisa membentuk konsep etnisitas bukan hanya sekadar padangan kesatuan suku tertentu tetapi lebih kepada kesatuan sebagai bangsa Indonesia (etnik Indonesia).
Hal-hal di atas memang bukan sesuatu yang aktual namun bila kita melihat secara lebih nyata lagi perbedaan budaya masih saja menjadi sumber konflik yang bisa saja terjadi. Karena itu bila kesadaran sebagai ‘satu’ dalam budaya yang sama ditanamkan secara dini, maka hal itu akan dengan mutlak menjadikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang bisa berkompetisi secara sehat dan positif dengan bangsa lain. Akhirnya penulis hanya bisa menulis dan sebagai implementasinya semuanya hanya terserah dari seluruh komponen bangsa yang memiliki loyalitas dan dedikasi penuh terhadap jati dirinya sendiri sebagai bangsa yang merdeka.
DAFTAR PUSTAKA
Alfian. 1985. Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia. Jakarta : LP3ES
Daliman, A. 1999. “Reorientasi Pendidikan Sejarah melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa”, Cakrawala Pendidikan. Edisi Khusus Mei Th. XVIII No. 2
Farkan, H. 1999. “Piagam Medinah dan Idealisme Masyarakat Madani”. Bernas, 29 Maret.
Gellner, E. 1995.Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan.(Terjemahan Hasan, I) Bandung: Mizan.
Hefner, R.W. 1998. “Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal”. Society,
Vol.35, No, 3 March/April
Hikam, A. S. 1999. Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society. Jakarta :
Penerbit Erlangga
Kartodirjo, S. 1999. Multi-Dimensi Pembangunan Bangsa : Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
Kleden, I. 1986. Sikap Ilmiah dan Kritik dan Kebudayaan. Jakarta : LP3S
Magnis-Suseno, F.1998. Mencari Makna Kebangsaan. Yogyakarta : Kanisius
Mangunwijaya, Y. B. 1998. Menuju Republik Indonesia Serikat. Jakarta : Gramedia
Mitakda, J. 2000. Etnosentrisme : Akar dan Tantangannya.Basis.Np.6-10. Mei
Nordholt, N. S. 1999. “Civil Society di Era Kegelisahan”. Basis. Np. 3-4. Maret.
Suharto, E. 2002. “Masyarakat Madani : Aktualisasi Profesionalisme Community
Workers dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadilan”. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_16.htm